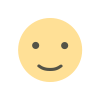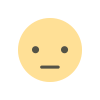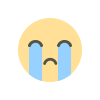Pilkada via DPRD Dinilai Ancaman Demokrasi, Dosen UGM: Rakyat Bisa Tersingkir dari Kekuasaan
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai kritik dari kalangan akademisi. Dosen Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, menilai kebijakan itu berisiko melemahkan posisi rakyat dan memperkuat elite politik. Ia menegaskan, mahalnya pilkada bukan disebabkan oleh mekanisme langsung, melainkan oleh buruknya tata kelola pendanaan politik.

RINGKASAN BERITA:
- Akademisi UGM menilai pilkada lewat DPRD berpotensi menggeser kedaulatan dari rakyat ke elite partai.
- Ongkos politik tinggi disebut bukan akibat pilkada langsung, melainkan praktik mahar politik dan politik uang.
- Solusi yang didorong adalah reformasi pendanaan politik, bukan penghapusan pilkada langsung.
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Rencana pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang mekanisme pemilihan kepala daerah kembali memantik perdebatan.
Usulan agar pilkada dilakukan melalui DPRD dinilai berpotensi mengubah arah demokrasi lokal dan mempersempit ruang partisipasi publik.
Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., menilai penghapusan hak pilih langsung warga justru akan menjauhkan masyarakat dari proses politik.
“Kalau dengan pilkada langsung saja aspirasi warga sering diabaikan, apalagi jika penentuan kepala daerah diserahkan ke DPRD. Itu berisiko mengeluarkan masyarakat dari sistem sosial-politik kita,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Alfath menjelaskan, meskipun anggota DPRD dipilih melalui pemilu, dalam praktiknya mereka tidak sepenuhnya lepas dari kepentingan elite partai.
Kondisi ini, menurutnya, membuka ruang semakin besarnya dominasi kelompok elite dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.
“DPRD tidak steril dari kepentingan elite partai. Jika pilkada dialihkan ke DPRD, yang menguat justru elite, bukan rakyat,” tegasnya.
Menanggapi alasan tingginya biaya pilkada, Alfath menyebut akar persoalan bukan terletak pada prosedur pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik yang menyimpang.
Ia mengurai bahwa ongkos besar muncul sejak proses pencalonan, kampanye, hingga sengketa hasil pemilihan.
“Biaya membengkak karena mahar politik, logistik kampanye, politik uang, bahkan pemungutan suara ulang dan perkara di Mahkamah Konstitusi. Ini bukan soal mekanisme demokratisnya, tetapi praktik informal yang ditoleransi,” jelasnya.
Ia menilai demokrasi elektoral Indonesia menghadapi problem struktural yang bersumber pada rendahnya kapasitas politisi, minimnya literasi politik publik, serta belum kuatnya politik berbasis program.
Menurutnya, mahar politik dan politik uang menciptakan cost spiral yang membuat ongkos pilkada terus melonjak.
Alfath juga menyoroti laporan dana kampanye yang dianggap tidak mencerminkan realitas di lapangan.
Ia menilai, transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik masih lemah sehingga persoalan biaya tidak pernah terselesaikan dari akarnya.
“Menghapus pilkada langsung itu mengobati gejala, bukan penyakit. Penyakitnya ada pada political financing,” katanya.
Sebagai alternatif, ia mendorong reformasi menyeluruh, mulai dari transparansi dana kampanye secara ketat dan real-time, pembenahan rekrutmen kandidat di internal partai, hingga penegakan hukum tegas terhadap praktik politik uang.
Ia juga membuka ruang peningkatan pendanaan negara bagi partai politik, dengan catatan pengawasan publik diperkuat.
“Jika negara menambah bantuan ke parpol, akuntabilitasnya harus naik. Peruntukannya jelas, misalnya untuk pendidikan politik dan kaderisasi,” ujarnya.
Alfath mengingatkan, jika kepala daerah dipilih DPRD, akuntabilitas kepemimpinan akan bergeser dari warga ke elite partai.
Hal ini dinilainya berpotensi meningkatkan praktik elite capture dan transaksi kebijakan pasca pemilihan.
Ia pun menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal isu ini.
“Debatnya harus digeser, bukan sekadar soal mahalnya demokrasi, tapi siapa yang sebenarnya diuntungkan dari perubahan mekanisme ini,” tuturnya.
Meski pilkada langsung dipertahankan, Alfath menegaskan ada tiga agenda mendesak yang harus dilakukan, yaitu pembatasan dan audit ketat dana kampanye, reformasi tata kelola serta rekrutmen kandidat partai, dan penegakan hukum politik uang tanpa tebang pilih.
“Tanpa tiga reformasi itu, pilkada langsung akan terus mahal dan rapuh dari sisi legitimasi demokratis,” pungkasnya. (*)