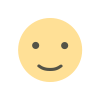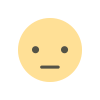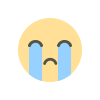Publik Menolak Keras Pilkada via DPRD, Akademisi UGM Bongkar Risiko Oligarki dan Politik Uang
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai penolakan luas dari masyarakat. Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik ingin kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Akademisi UGM menilai narasi efisiensi biaya tidak berbasis data dan justru berpotensi memperkuat oligarki serta merusak kualitas demokrasi lokal.

RINGKASAN BERITA:
- Hanya 5,6 persen warga setuju Pilkada lewat DPRD, 77,3 persen ingin tetap dipilih rakyat
- Akademisi UGM menilai wacana ini sarat kepentingan elite dan berpotensi menguatkan oligarki
- Riset menunjukkan biaya politik tidak akan hilang, hanya bergeser bentuk dan titik transaksinya.
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Gelombang penolakan publik menguat terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, hanya 5,6 persen responden yang menyatakan setuju, sementara 77,3 persen dengan tegas menghendaki agar kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Sorotan tajam juga datang dari kalangan akademisi. Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati, menilai alasan yang kerap dikemukakan partai politik, seperti efisiensi biaya dan penekanan korupsi, tidak disertai dasar ilmiah yang memadai.
“Narasi dan argumentasi itu tidak didukung dengan data. Tidak ada data dan tidak ada simulasinya,” ujar Mada dilansir dari portal resmi UGM, Senin (19/1/2026).
Menurutnya, klaim bahwa Pilkada via DPRD akan lebih murah dan mampu menekan korupsi politik masih sebatas asumsi.
Ia menegaskan bahwa seluruh dalih tersebut seharusnya diuji secara terbuka melalui riset dan simulasi kebijakan yang transparan.
Lebih jauh, Mada mencurigai adanya mens rea atau niat tersembunyi di balik wacana pemilihan di ruang tertutup.
Ia memandang mekanisme ini berpotensi menjadi jalan sistematis untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu.
“Publik saya kira juga mencurigai. Mens rea dari ide ini adalah untuk memperkuat oligarki dan sistem politik kartel. Termasuk juga untuk melakukan resentralisasi dari pembangunan pusat,” tuturnya.
Menampik anggapan bahwa Pilkada langsung identik dengan pemborosan, Mada memaparkan hasil riset kolaborasi DPP Fisipol UGM, KITLV Leiden, dan Universitas Ahmedabad terkait pendanaan kampanye Pilkada 2024.
Dari 14 kabupaten/kota dan 7 provinsi, ditemukan bahwa alokasi mahar politik untuk tiket pencalonan berada di kisaran 10 persen, sementara politik uang mencapai 26 persen.
Dari temuan tersebut, Mada mempertanyakan efektivitas pemilihan lewat DPRD dalam menekan biaya politik. Ia justru melihat risiko meningkatnya transaksi elite.
“Kalau ini dipilih melalui DPRD, pertanyaannya apakah kemudian uang mahar politik itu justru akan meningkat persentasenya?” ucapnya.
Ia menambahkan, skema tidak langsung bukan menghapus biaya gelap, melainkan berpotensi memindahkan praktik vote buying ke ruang yang lebih sempit.
“Alih-alih hilang, justru ada kemungkinan alokasi untuk vote buying akan dipindah ke alokasi mahar politik atau membeli dukungan saat proses pemilihan di DPRD,” tambah Mada.
Selain soal biaya, Mada menyoroti ancaman serius terhadap kualitas demokrasi lokal.
Menurutnya, kepala daerah hasil pilihan DPRD berpotensi menjadi subordinat lembaga legislatif daerah, sekaligus mempersempit ruang kompetisi politik.
“Peluang anak muda, masyarakat marginal, atau masyarakat biasa itu menjadi sangat tipis karena kompetisi terbatas hanya di kalangan elite,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Mada mendorong negara untuk tidak kembali ke sistem lama, melainkan memperbaiki tata kelola Pilkada langsung.
“Solusinya adalah memperkuat mekanisme pendanaan kampanye untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Pilihan lainnya adalah menerapkan Pilkada langsung secara asimetris, meskipun indikatornya perlu dimatangkan,” pungkasnya. (*)