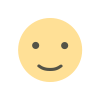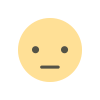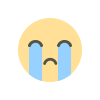Akar Ekstremisme Berkaitan dengan Disintegrasi Psikologis
Mahasiswa doktor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Haykal Hafizul Arifin, mengungkapkan bahwa ekstremisme tidak semata dipicu paparan ideologi radikal, melainkan berakar pada kondisi psikologis disintegrasi. Temuan ini disampaikannya dalam sidang terbuka promosi doktoral di UI, Depok.

RINGKASAN BERITA:
-
Akar ekstremisme tidak hanya dipicu ideologi radikal, tetapi juga kondisi disintegrasi psikologis.
-
Perasaan berdosa yang tidak terkelola dapat mendorong ekstremisme, sementara pengampunan memperkuat ketahanan diri.
-
Deradikalisasi perlu fokus pada pemulihan psikologis, bukan semata pendekatan represif.
RIAUCERDAS.COM, DEPOK - Akar ekstremisme tidak hanya berasal dari paparan paham radikal, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis yang disebut sebagai disintegrasi.
Kondisi ini ditandai oleh ketidakstabilan emosi, kehilangan tujuan hidup, serta kekacauan pikiran.
Paparan tersebut disampaikan Mahasiswa doktor Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Haykal Hafizul Arifin dalam sidang terbuka promosi doktoral yang digelar di Aula Gedung D Fakultas Psikologi UI, Depok, Rabu (7/1/2026) lalu.
Dalam disertasinya berjudul “Disintegrasi Psikologis pada Mindset Ekstremis”, ia menjelaskan bahwa kekerasan kerap dipilih individu sebagai jalan pintas untuk meredakan konflik batin yang mendalam.
Melalui lima studi empiris, Haykal menemukan bahwa individu dengan kondisi disintegrasi psikologis cenderung mencari solusi yang cepat dan drastis terhadap masalah hidup yang dihadapi.
Dalam konteks ini, kekerasan dipersepsikan sebagai sarana pemulihan diri yang paling pasti.
“Kekerasan dianggap memiliki daya pemulihan yang paling pasti bagi mereka yang merasa jiwanya tidak utuh,” ujar Haykal dilansir dari portal resmi UI pada Minggu (18/1/2026).
Temuan tersebut diperkuat dengan pengembangan alat ukur baru bernama Militant Extremist Mindset Scale, yang dinilai akurat dalam memetakan pola pikir ekstrem baik pada masyarakat umum maupun narapidana terorisme.
Salah satu aspek penting dalam riset ini adalah peran perasaan berdosa dalam konteks keagamaan.
Haykal menjelaskan bahwa individu yang merasa gagal memenuhi standar moral agama kerap mengalami konflik psikologis yang berat.
Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat membuka ruang masuknya narasi ekstremisme yang menawarkan kekerasan sebagai jalan penebusan dosa.
Sebaliknya, individu yang mempraktikkan pertobatan secara rutin dan memaknai pengampunan Tuhan secara personal menunjukkan ketahanan psikologis yang lebih kuat terhadap ajakan ekstremisme.
Rasa ampun, menurut Haykal, mampu meredam dorongan untuk melakukan pengorbanan diri yang bersifat destruktif.
Haykal menegaskan bahwa paparan ideologi ekstrem tidak otomatis menghasilkan radikalisasi.
Dampaknya sangat bergantung pada kondisi kesehatan psikologis individu.
Oleh karena itu, upaya pencegahan dan deradikalisasi dinilai perlu melampaui pendekatan represif dan kontra-ideologis, dengan fokus pada pemulihan keseimbangan psikologis dan pencarian makna hidup yang tidak berbasis kekerasan.
“Paparan ideologi radikal tidak otomatis membuat seseorang menjadi ekstremis. Semua bergantung pada kondisi kesehatan jiwanya,” kata Haykal.
Dalam sidang promosi doktor tersebut, Haykal dipromotori oleh Prof. Dr. Mirra Noor Milla, Prof. Dr. Bagus Takwin, dan Ali Mashuri, Ph.D. (*)