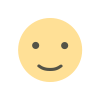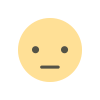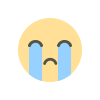Riset Dosen UMM Ungkap 8.000 Hoaks Vaksin, Infodemik Disebut Sama Bahayanya dengan Pandemi
Dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Nasrullah, meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia lewat riset tentang model komunikasi pemerintah di media sosial untuk memitigasi infodemik. Penelitiannya menemukan lebih dari 8.000 hoaks vaksin dan menekankan pentingnya respons cepat serta ekosistem informasi positif.

RINGKASAN BERITA:
- Dosen UMM meraih doktor di UPSI Malaysia lewat riset mitigasi infodemik melalui Government Social Media.
- Penelitian menemukan lebih dari 8.000 hoaks vaksin dengan pola narasi ilmiah semu dan konspiratif.
- Strategi yang ditawarkan mencakup deteksi dini, respons cepat, dan kolaborasi dengan Mafindo untuk memperkuat literasi digital.
RIAUCERDAS.COM, MALANG - Gelombang disinformasi di media sosial kembali menjadi perhatian, terutama pada isu kesehatan dan kebijakan publik.
Fenomena yang disebut sebagai infodemik ini menjadi fokus riset dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Nasrullah, M.Si., Ph.D., yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia.
Dalam disertasinya, Nasrullah meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam meredam dampak infodemik, khususnya saat pandemi Covid-19.
Ia menyoroti bagaimana arus hoaks vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru hingga memicu penolakan terhadap program kesehatan nasional.
“Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era media sosial, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” kata Nasrullah dilansir dari situs UMM, Jumat (13/2/2026).
Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber beragam.
Narasi yang muncul tak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi hingga informasi yang dipelintir agar tampak ilmiah.
“Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang memakai bahasa ilmiah semu, ada yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” ujarnya.
Penelitian tersebut juga mengungkap bahwa polarisasi politik mempercepat penyebaran disinformasi.
Pada masa pandemi, afiliasi politik memengaruhi cara publik menafsirkan pesan kesehatan pemerintah.
“Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, tapi isu politik,” ungkapnya.
Menurut Nasrullah, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah tidak berjalan optimal karena harus menghadapi narasi tandingan yang masif.
Rendahnya literasi informasi masyarakat juga dinilai memperbesar kerentanan terhadap konten menyesatkan.
Sebagai solusi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis yang mencakup langkah preventif dan reaktif.
Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif melalui respons cepat terhadap hoaks yang beredar.
“Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus punya sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” jelasnya.
Ia menegaskan, meski pandemi telah mereda, ancaman infodemik tetap ada dan dapat muncul pada isu kebijakan baru, kesehatan, maupun teknologi.
“Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya.
Nasrullah juga mendorong kolaborasi multipihak, termasuk dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), guna memperkuat literasi digital masyarakat.
Ia menilai pengelolaan informasi harus diposisikan sama pentingnya dengan penanganan medis dalam situasi krisis global.
“Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya. (*)