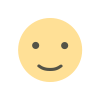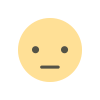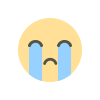IHSG Ambruk dan Trading Halt, Krisis Kepercayaan Pasar Jadi Sorotan Akademisi
Kejatuhan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2026 dinilai bukan sekadar koreksi pasar, melainkan refleksi krisis kepercayaan investor terhadap tata kelola pasar modal Indonesia. Akademisi UGM menilai transparansi dan regulasi menjadi kunci pemulihan.

RINGKASAN BERITA:
- Keputusan MSCI memicu gelombang jual investor asing
- Minimnya transparansi dinilai memperparah kejatuhan IHSG
- OJK dan BEI didesak memperkuat tata kelola dan keterbukaan
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Gejolak hebat mengguncang pasar modal Indonesia menjelang akhir Januari 2026 setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas dari level tertingginya sepanjang masa.
Pada 29 Januari 2026, indeks terkoreksi lebih dari delapan persen dalam satu hari perdagangan, memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan trading halt akibat tekanan jual yang masif.
Padahal sebelumnya IHSG sempat mencetak rekor di level 9.134,70.
Kejatuhan mendadak tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan pelaku pasar dan memicu pertanyaan mengenai ketahanan serta kredibilitas pasar modal nasional.
Guru Besar Keuangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. rer. soc. R. Agus Sartono, M.B.A., menilai anjloknya IHSG tidak dapat dilepaskan dari memburuknya persepsi investor global terhadap transparansi pasar Indonesia.
Menurutnya, keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menerapkan interim freeze terhadap penilaian saham Indonesia menjadi pemicu utama reaksi berantai di pasar.
Langkah tersebut dinilai merusak ekspektasi pertumbuhan jangka pendek dan memperbesar ketidakpastian.
Agus menjelaskan, MSCI menyoroti keterbatasan keterbukaan data terkait struktur kepemilikan saham, tingginya konsentrasi kepemilikan pada emiten besar, hingga penutupan informasi kode broker dan domisili selama jam perdagangan.
Kondisi tersebut, ditambah potensi penerapan full call auction pada saham tertentu, membuat proses pembentukan harga dianggap tidak transparan.
Dilansir dari portal UGM, Agus menyampaikan bahwa situasi ini mendorong investor asing melakukan aksi jual besar-besaran.
Pada 28 Januari 2026, investor asing mencatatkan penjualan bersih sekitar Rp6,17 triliun, yang berlanjut keesokan harinya dengan net sell sekitar Rp4,63 triliun.
Tekanan tersebut membuat pasar menjadi tipis (thin market) dan semakin rentan terhadap gejolak harga.
Alih-alih menenangkan pasar, rangkaian pengunduran diri pimpinan otoritas justru memperdalam ketidakpastian.
Mundurnya Direktur Utama BEI pada 30 Januari 2026, disusul pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi pada hari yang sama, dinilai memperburuk sentimen pasar.
Agus menegaskan, reaksi cepat investor berakar pada ekspektasi terhadap kemampuan aset menghasilkan arus kas di masa depan.
Ketika kepercayaan terhadap nilai wajar saham terganggu, investor cenderung menarik dana untuk menghindari risiko yang lebih besar.
Ia juga menyoroti kekhawatiran bahwa sebagian transaksi di pasar tidak mencerminkan nilai fundamental, melainkan dipengaruhi oleh kepemilikan mayoritas dan minimnya partisipasi investor ritel.
Fenomena perilaku ikut-ikutan atau herding, termasuk FOMO di kalangan investor domestik, turut mempercepat tekanan jual.
Menurut Agus, kejatuhan IHSG kali ini mencerminkan tuntutan global terhadap standar tata kelola yang lebih tinggi.
Dalam kondisi tersebut, OJK dan BEI menghadapi tantangan besar untuk memperbaiki regulasi free float dan menguatkan keterbukaan pemilik manfaat guna memulihkan kepercayaan.
Ia menekankan bahwa pasar modal seharusnya menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian.
Namun hal itu hanya dapat terwujud jika kualitas emiten terjaga dan informasi keuangan disajikan secara utuh dan transparan.
Agus juga mendorong peninjauan ulang kebijakan yang memperbolehkan perusahaan dengan arus kas bebas negatif melakukan penawaran umum perdana saham (IPO).
Pengalaman IPO sejumlah startup dengan arus kas negatif yang berujung pada kejatuhan harga saham menjadi pelajaran penting bagi regulator dan investor.
Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, Agus menilai pendekatan valuasi berbasis Free Cash Flow (FCF) menjadi semakin relevan.
Berbeda dengan laba bersih yang mudah dipengaruhi kebijakan akuntansi, FCF mencerminkan kemampuan riil perusahaan menghasilkan kas dan menjaga keberlanjutan usaha.
“FCF dapat menjadi sinyal peringatan dini bagi investor. Jika laba terlihat positif tetapi arus kas negatif, itu patut dicermati,” ujarnya.
Krisis pasar pada akhir Januari 2026, menurut Agus, menjadi pengingat bahwa keterbukaan dan integritas adalah fondasi utama pasar modal.
Tanpa keduanya, pasar akan terus rentan terhadap guncangan dan sulit menjalankan perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (*)