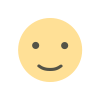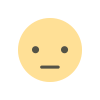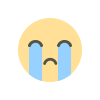Pakar Gizi UGM Nilai Program MBG Masih Rawan Masalah, Soroti Risiko Keracunan dan Bom Waktu Penyakit
Setahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pakar gizi UGM menilai program ini masih memerlukan banyak evaluasi, terutama terkait pengawasan keamanan pangan dan komposisi menu. Kasus keracunan massal serta penggunaan makanan ultra proses menjadi sorotan karena dinilai berisiko bagi kesehatan jangka panjang anak. Meski demikian, MBG tetap dipandang sebagai investasi gizi penting menuju Indonesia Emas 2045.

RINGKASAN BERITA :
- Pakar UGM menilai MBG program mulia, tetapi masih lemah pada pengawasan keamanan pangan.
- Penggunaan ultra processed food (UPF) disebut berpotensi jadi “bom waktu” penyakit kronis.
- Pemanfaatan pangan lokal dan fleksibilitas kebijakan dinilai kunci keberhasilan MBG jangka panjang.
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Setelah setahun diimplementasikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar.
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, menegaskan bahwa program ini membutuhkan evaluasi serius, khususnya dalam aspek keamanan pangan dan kualitas menu.
Mirza menyampaikan bahwa secara konsep, program school lunch seperti MBG memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni mencetak generasi masa depan yang sehat dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menekankan bahwa program serupa telah lama diterapkan di berbagai negara sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya.
“Terlepas dari agenda politik, program school lunch ini sudah diterapkan di berbagai dunia dan memang menjadi agenda wajib negara untuk memperbaiki gizi generasi mudanya,” ungkap Mirza dilansir dari portal resmi UGM.
Namun dalam praktiknya, ia menilai masih terdapat anomali dan kontroversi, salah satunya munculnya kasus keracunan massal yang diduga berkaitan dengan lemahnya pengawasan proses penyiapan makanan.
Menurutnya, pengawasan ketat terhadap seluruh rantai produksi makanan harus menjadi prioritas utama.
Mirza mengusulkan agar sekolah diberi peran lebih besar dalam penyediaan makan siang.
Dengan cakupan yang lebih kecil, sekolah dinilai lebih mampu melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, hingga distribusi kepada siswa.
“Dengan skala yang lebih kecil, kesalahan distribusi dan keamanan pangan bisa lebih terminimalisir,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan makanan memiliki aturan baku yang harus mengacu pada regulasi Kementerian Kesehatan, termasuk penggolongan kelompok berisiko tinggi.
Anak sekolah dan ibu hamil, kata dia, termasuk kelompok yang penanganannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
“Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” tegas Mirza.
Sorotan lain diarahkan pada penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu MBG.
Mirza menilai hal ini bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan terkait pengurangan gula, garam, dan lemak.
“Anak-anak diberi UPF, di situ ada natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin tidak terlihat sekarang, tapi 10–15 tahun ke depan akan menjadi bom waktu penyakit kronis,” jelasnya.
Meski demikian, Mirza menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa diukur dalam waktu singkat.
Dampak investasi gizi, menurutnya, baru dapat terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10 hingga 15 tahun mendatang.
Ia juga mendorong agar kebijakan MBG membuka ruang lebih luas bagi pemanfaatan bahan pangan lokal yang beragam sesuai karakteristik daerah.
Menurutnya, penyeragaman menu, apalagi berbasis UPF, justru berisiko tidak cocok dengan kondisi tubuh dan budaya makan anak di setiap wilayah.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.
Sebagai langkah perbaikan, Mirza menekankan tiga hal utama. Pertama, penegakan ketat keamanan pangan disertai sanksi tegas bagi pihak yang lalai.
Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk memantau dampak MBG terhadap status kesehatan anak, mulai dari indikator kebugaran hingga antropometri.
Ketiga, kebijakan MBG harus bersifat fleksibel dan terbuka terhadap temuan ilmiah.
“Kalau ada bukti ilmiah yang menunjukkan perlu perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkasnya. (*)