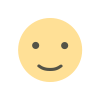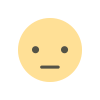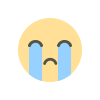Waspada Infodemic: Guru Besar UGM Ingatkan Bahaya Misinformasi Kesehatan di Media Sosial
Kemudahan akses informasi kesehatan di media sosial menyimpan risiko serius akibat tingginya misinformasi. Guru Besar Fakultas Farmasi UGM Prof. Zullies Ikawati menekankan pentingnya literasi kesehatan dan digital agar masyarakat tidak terjebak hoaks yang berpotensi membahayakan.

RINGKASAN BERITA:
-
Infodemic berlanjut. Misinformasi kesehatan di media sosial masih tinggi, terutama soal obat, vaksin, dan terapi.
-
Masyarakat perlu literasi kesehatan dan digital untuk menyaring informasi.
-
Dokter dan akademisi perlu aktif mengisi ruang digital dengan edukasi berbasis bukti.
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Media sosial kini menjadi rujukan utama masyarakat dalam mencari informasi kesehatan, mulai dari tips pola makan hingga klaim khasiat obat dan terapi alternatif.
Namun, derasnya arus informasi tersebut tidak selalu sejalan dengan pedoman klinis standar, sehingga menuntut sikap bijak dan kritis dari masyarakat.
Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. apt. Zullies Ikawati, Ph.D., mengingatkan bahwa di balik kemudahan akses informasi, tersembunyi persoalan serius karena tidak semua konten kesehatan di media sosial bersifat akurat. Bahkan, sebagian informasi justru berpotensi membahayakan.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak pandemi COVID-19 telah memperkenalkan istilah infodemic, yakni kondisi banjir informasi yang bercampur antara fakta, opini, dan hoaks, sehingga menyulitkan masyarakat membedakan informasi yang benar dan menyesatkan.
“Hal ini dapat menimbulkan kebingungan, mendorong perilaku berisiko, serta menurunkan kepercayaan pada otoritas kesehatan,” ujar Zullies dilansir dari portal resmi UGM, Rabu (14/1/2026).
Menurut Zullies, fenomena tersebut tidak berhenti setelah pandemi mereda, tetapi terus berlanjut dalam berbagai isu kesehatan sehari-hari, seperti klaim obat “ajaib” dan terapi alternatif tanpa dasar ilmiah.
Sejumlah studi menunjukkan tingginya proporsi misinformasi kesehatan di media sosial, terutama pada topik obat, vaksin, dan penyakit kronis.
Ia menyebutkan, pada isu rokok dan produk terkait serta obat-obatan tertentu, misinformasi di media sosial bahkan dapat mencapai 87 persen.
Sementara itu, misinformasi vaksin berkisar 43 persen, penyakit termasuk kanker dan pandemi sekitar 40 persen, serta tindakan atau terapi medis sekitar 30 persen.
Kondisi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung mengangkat konten sensasional dan emosional.
Di Indonesia, persoalan serupa tercermin dari data penanganan hoaks pemerintah.
Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat hingga akhir 2023 telah menangani 12.547 isu hoaks, dengan 2.357 di antaranya bertema kesehatan.
Isu kesehatan kerap dimanfaatkan karena mudah memicu emosi, kepanikan, dan harapan kesembuhan instan, sehingga cepat viral.
Zullies juga menyoroti tantangan pada produk kesehatan, di mana informasi sering bercampur dengan promosi.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara berkala merilis hasil pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu.
Pada semester I 2025, BPOM mencatat temuan 79.015 konten obat dan makanan ilegal di e-commerce.
“Informasi kesehatan di ruang digital tidak bisa dipandang netral karena sering beririsan dengan kepentingan komersial. Kunci utamanya adalah literasi kesehatan dan literasi digital,” tegas Zullies.
Ia menjelaskan, informasi kesehatan yang dapat dipercaya umumnya memiliki sumber jelas, disampaikan oleh pihak kompeten, menggunakan bahasa proporsional, serta menyebutkan manfaat dan risiko secara seimbang.
Sebaliknya, masyarakat perlu mewaspadai klaim yang terlalu pasti, menjanjikan hasil instan, atau menyatakan “aman untuk semua orang” tanpa pengecualian.
Zullies menambahkan, masyarakat dapat melakukan filter sederhana dengan mengecek identitas dan kompetensi sumber, mewaspadai kata-kata seperti “100 persen aman” atau “dokter tidak mau kamu tahu”, serta memahami konteks informasi, termasuk siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan suatu intervensi kesehatan.
Ia juga menegaskan peran strategis tenaga kesehatan dalam mengisi ruang media sosial dengan edukasi yang benar dan empatik.
Kehadiran dokter, apoteker, dan akademisi dinilai penting untuk membantu masyarakat memahami batasan informasi digital dan kapan harus mencari pertolongan profesional.
“Media sosial bukan untuk dimusuhi, tetapi juga bukan satu-satunya rujukan kebenaran. Dalam urusan kesehatan, kehati-hatian adalah wujud tanggung jawab,” pungkasnya. (*)