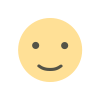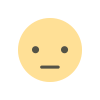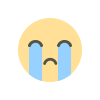Bukan Sekadar Angka, Penyusutan Kelas Menengah Dinilai Ganggu Optimisme Sosial
Jumlah kelas menengah Indonesia menyusut 1,2 juta orang dalam setahun menurut laporan Mandiri Institute. Ekonom UGM menilai tren ini mengancam mobilitas sosial dan optimisme masyarakat. Kualitas pekerjaan dan tekanan biaya hidup disebut sebagai faktor utama penyebab penyusutan.

RINGKASAN BERITA:
- Kelas menengah turun dari 47,9 juta menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
- Kelompok aspiring middle class meningkat dan rentan jatuh akibat guncangan ekonomi.
- Ekonom menilai kualitas pekerjaan dan minim perlindungan sosial sebagai akar masalah.
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Penyusutan jumlah kelas menengah di Indonesia dinilai bukan sekadar fenomena statistik, melainkan sinyal melemahnya mobilitas sosial.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Wisnu Setiadi Nugroho, menilai tren ini dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan optimisme masyarakat.
Berdasarkan laporan Mandiri Institute, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Proporsinya terhadap total penduduk ikut menurun dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen.
Di saat yang sama, kelompok aspiring middle class (AMC) justru meningkat 4,5 juta jiwa dan kini mencakup 50,4 persen populasi.
Menurut Wisnu, membesarnya kelompok AMC menunjukkan semakin banyak keluarga berada di ambang ketidakpastian ekonomi.
Kelompok ini dinilai dekat untuk naik kelas, namun juga sangat rentan turun jika terkena guncangan seperti PHK, kenaikan biaya pendidikan, atau beban cicilan.
“Membesarnya AMC hari ini mencerminkan betapa banyak keluarga yang kini berdiri di tepi jurang ketidakpastian,” ujarnya dikutip dari situs UGM, Rabu (18/2/2026).
Ia menegaskan, penyusutan kelas menengah menggerus rasa aman masyarakat terhadap masa depan.
“Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan"
Wisnu menjelaskan, salah satu penyebab utama adalah kualitas lapangan kerja yang tidak cukup mendorong mobilitas.
Banyak pekerjaan baru bersifat survival-based, yang hanya cukup untuk bertahan hidup tanpa menjanjikan stabilitas pendapatan atau jenjang karier.
“Ekonomi gig, kerja informal, dan pekerjaan berproduktivitas rendah memang menyerap tenaga kerja. Namun pekerjaan seperti ini jarang menyediakan stabilitas pendapatan, jaminan sosial, atau jalur karier yang jelas. Orang bekerja keras, tetapi tangga sosialnya tidak bertambah panjang,” terangnya.
Selain faktor pekerjaan, tekanan terhadap daya beli juga dinilai menjadi pemicu.
Upah riil kelas menengah bawah relatif stagnan, sementara biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi terus meningkat.
Tekanan ini disebut sebagai income squeeze yang secara perlahan menggerus kemampuan menabung dan merencanakan masa depan.
Wisnu juga menyoroti minimnya bantalan perlindungan bagi kelompok hampir menengah.
Banyak pekerja rentan tidak memiliki jaminan sosial, sehingga satu guncangan kecil dapat menjatuhkan stabilitas ekonomi keluarga.
“Kita belum memiliki shock absorber yang memadai bagi kelompok nyaris menengah. Kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang tentu saja masih harus dilindungi. Namun AMC yang kini menjadi mayoritas populasi berada dalam wilayah abu-abu. Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup aman untuk mandiri sepenuhnya. Bisa dibilang mereka berdiri sendirian ketika risiko datang. Jika tren ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial,” tuturnya.
Ia memperingatkan risiko aspiration without mobility, yakni kondisi ketika aspirasi masyarakat tinggi namun tidak diikuti jalur mobilitas yang jelas.
Jika tren ini berlanjut, fondasi konsumsi dan basis pajak berpotensi melemah.
“Pertumbuhan ekonomi penting, namun pertumbuhan tanpa kualitas pekerjaan adalah pertumbuhan yang rapuh. Produk Domestik Bruto (PDB) bisa naik, tetapi jika mobilitas macet, harapan sosial ikut membeku,” imbuhnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wisnu menilai pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi, memperkuat keterhubungan pendidikan vokasi dengan industri, serta memperluas jaminan sosial bagi pekerja non-formal.
Skema pembiayaan perumahan dan pendidikan juga dinilai perlu diperkuat agar kelompok near-middle tidak mudah tergelincir akibat satu guncangan ekonomi.
Ia menambahkan, kebijakan publik harus diarahkan untuk membuka mobilitas, bukan sekadar redistribusi jangka pendek.
“Kelas menengah bukan hanya kategori statistik. Ia adalah penyangga stabilitas, sumber konsumsi, pembayar pajak, dan yang paling penting, penjaga optimisme sosial. Jika mesin mobilitas sosial terus melambat, yang hilang bukan sekadar angka 1,2 juta,” kata dia. (*)