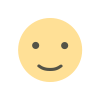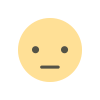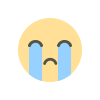Indeks Kemerdekaan Pers Naik, Akademisi UGM Ingatkan Ancaman Intervensi Kekuasaan
Indeks Kemerdekaan Pers 2025 naik menjadi 69,44 dan masuk kategori bebas. Namun akademisi UGM menilai kebebasan pers Indonesia masih rentan terhadap intervensi kekuasaan dan belum sepenuhnya menghormati prosedur jurnalistik.

RINGKASAN BERITA:
- Indeks Kemerdekaan Pers 2025 naik 0,8 persen dan masuk kategori bebas.
- Akademisi UGM menilai pers Indonesia masih dekat dengan kategori “cukup bebas”.
- Respons pemerintah terhadap laporan media dinilai belum menghormati UU Pers.
RIAUCERDAS.COM, YOGYAKARTA - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2026 diwarnai kabar meningkatnya Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia.
Meski masuk kategori bebas, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal, terutama dalam relasi antara media pers dan kekuasaan.
Berdasarkan hasil riset Litbang Kompas, Indeks Kemerdekaan Pers 2025 tercatat naik 0,8 persen menjadi 69,44.
Guru Besar Jurnalisme Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Ana Nadhya Abrar., M.E.S, menyebut angka tersebut telah masuk kategori bebas, mengingat indeks kemerdekaan pers dibagi ke dalam tiga kategori, yakni tidak bebas (0–30), cukup bebas (31–60), dan bebas (61–100).
Meski demikian, Abrar menilai capaian tersebut belum sepenuhnya menggembirakan. Menurutnya, posisi pers Indonesia masih lebih dekat ke kategori “cukup bebas” dibandingkan kondisi ideal kebebasan pers.
“Yang terpenting segera menyusun road map memperjuangkan kebebasan pers.,” katanya dilansir dari situs UGM, Rabu (11/2/2026).
Abrar menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kebebasan pers tidak hanya berada di pundak jurnalis dan perusahaan media.
Masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan wartawan dapat bekerja secara bebas dan aman.
Menurutnya, berbagai upaya dapat dilakukan untuk menjamin kebebasan pers, mulai dari membangun solidaritas antara masyarakat dan wartawan, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kesadaran publik, hingga bekerja sama dengan lembaga yang konsisten memperjuangkan kebebasan pers.
“Bisa dilakukan pula dengan mencari perlindungan dari lembaga yang berwenang,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan kebebasan pers oleh masyarakat sipil merupakan hal yang wajar, mengingat media pers bekerja untuk kepentingan publik.
Meski media memperoleh keuntungan secara ekonomi dari profesionalismenya, Abrar menilai hal tersebut bukan tujuan utama.
“Tujuan utama kerja media pers adalah melayani kebenaran untuk kebaikan masyarakat,” terangnya.
Dalam praktik jurnalistik, Abrar mengakui media pers kerap berhadapan dengan berbagai kekuatan, mulai dari lembaga pemerintah, kelompok kepentingan, pengusaha, hingga kelompok radikal atau ekstremis.
Menurutnya, pihak-pihak tersebut memiliki potensi melakukan kekerasan terhadap wartawan dan melanggar kebebasan pers, sekaligus beririsan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
“Itulah sebabnya kegiatan memperjuangkan kebebasan pers perlu dibarengi dengan memperjuangkan HAM. Tegasnya, istilahnya menjadi memperjuangkan kebebasan pers dan HAM,” paparnya.
Selain tekanan eksternal, Abrar menilai media pers juga memiliki tanggung jawab internal untuk melindungi kemerdekaan wartawan.
Ia menekankan pentingnya memberikan ruang gerak luas bagi jurnalis agar independen, melindungi sumber informasi dan privasi wartawan, serta menghormati hak masyarakat untuk mengetahui dan menyampaikan pendapat.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan standar etika jurnalistik yang tinggi serta larangan terhadap penyensoran atau pembatasan konten media.
“Dalam hubungan ini, tentu saja pemerintah tidak boleh berlaku kasar terhadap media pers, tidak boleh menjadikan media pers sebagai musuh politik dan bisa menghargai prosedur jurnalisme yang standar,” ujarnya.
Namun, Abrar menilai prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya dipatuhi pemerintah.
Ia mencontohkan respons pemerintah terhadap laporan utama Majalah Tempo edisi 2–8 Februari 2026 yang menyebut Presiden Prabowo dan rombongan menggunakan dua pesawat Garuda Indonesia dengan fasilitas first class saat kunjungan luar negeri.
Dalam kasus tersebut, pemerintah tidak menggunakan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.
Melalui Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, pemerintah langsung menyatakan bahwa laporan tersebut tidak benar.
Bagi Abrar, langkah tersebut merupakan pendekatan politik yang mengabaikan prosedur jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 dan 6 terkait hak jawab dan hak koreksi.
“Dalam keadaan begini, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya persepsi pemerintah tentang kebebasan pers. Ketidaktahuan ini mengantarkan kita untuk bertanya, betulkah pemerintah menghargai kebebasan pers? Bisakah kita berharap kepada pemerintah untuk ikut memperjuangkan kebebasan pers di Indonesia?,” pungkasnya. (*)