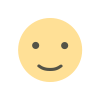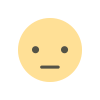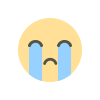Riset BRIN: Pendidikan Ibu Rendah Tingkatkan Risiko Gagal ASI Eksklusif hingga 8,8 Kali
Riset BRIN menemukan pendidikan ibu rendah, status kerja, dan praktik prelakteal menjadi faktor utama kegagalan ASI eksklusif. Studi ini menegaskan pentingnya intervensi berbasis keluarga dan kebijakan ramah ibu menyusui.

RINGKASAN BERITA:
- Ibu berpendidikan rendah berisiko 8,84 kali gagal memberi ASI eksklusif.
- Praktik prelakteal meningkatkan risiko hingga 5,67 kali.
- Faktor sosial, budaya, dan gender memengaruhi keberhasilan menyusui.
RIAUCERDAS.COM - Riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap faktor-faktor utama yang meningkatkan risiko bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif.
Studi ini menemukan bahwa tingkat pendidikan ibu menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi praktik menyusui.
Penelitian yang dilakukan peneliti BRIN, Yuly Astuti, menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan SMP atau lebih rendah memiliki peluang 8,84 kali lebih besar tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu berpendidikan perguruan tinggi.
Sementara itu, anak dari ibu bekerja memiliki risiko 6,45 kali lebih tinggi tidak mendapatkan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja.
Studi dari Pusat Riset Kependudukan BRIN ini menggunakan pendekatan mixed-methods dengan melibatkan 706 ibu yang memiliki anak usia 6–59 bulan.
“Hasil analisis menunjukkan 58,1% anak dalam sampel tidak menerima ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Angka yang mencerminkan masih kuatnya hambatan struktural dan sosial dalam praktik menyusui,” ujar Yuly dilansir situs BRIN, Sabtu (21/2/2026).
Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan ibu, status pekerjaan, serta praktik pemberian makanan atau minuman prelakteal menjadi determinan paling dominan dalam praktik menyusui di Kabupaten Karanganyar.
Salah satu temuan penting adalah praktik prelakteal, yakni pemberian madu atau gula pada bayi baru lahir.
Kebiasaan ini meningkatkan risiko tidak diberikannya ASI eksklusif hingga 5,67 kali.
Sekitar 36,1% responden mengaku melakukan praktik tersebut, umumnya karena keyakinan budaya bahwa rasa manis membawa kebaikan bagi anak.
“Data kami menunjukkan bahwa praktik prelakteal bukan sekadar kebiasaan, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kegagalan ASI eksklusif. Ini menjadi titik intervensi yang sangat strategis,” jelas Yuly.
Selain itu, penelitian juga menemukan faktor sosial lain yang berpengaruh.
Anak laki-laki lebih berisiko tidak menerima ASI eksklusif dibandingkan anak perempuan, dan anak dari keluarga berpendapatan rendah juga memiliki peluang lebih besar mengalami praktik non-ASI eksklusif.
Temuan ini mengindikasikan adanya dimensi sosial, ekonomi, dan konstruksi gender yang memengaruhi pola pengasuhan bayi, dan jenis kelamin anak turut mempengaruhi pemberian ASI eksklusif di lokasi penelitian.
"Cara pandang bahwa anak laki-laki penerus keluarga, harus sehat dan tidak cukup hanya diberikan ASI, sehingga menurut ibu-ibu di lokasi penelitian, anak laki-laki harus diberikan makanan lainnya sebelum waktunya,“ papar Yuly.
Menurutnya, konstruksi gender menjadi salah satu faktor yang memicu kegagalan pemberian ASI eksklusif.
Tantangan menyusui juga tidak bisa dilihat sebagai persoalan individu ibu semata, melainkan dipengaruhi lingkungan keluarga.
“Keputusan menyusui sering kali berada dalam ruang negosiasi keluarga. Ada persepsi bahwa bayi yang lebih besar dianggap lebih sehat, sehingga ibu didorong memberi susu formula atau makanan tambahan lebih awal,” ujar Yuly.
Yuly menegaskan bahwa kebijakan dan promosi kesehatan perlu berbasis bukti serta sensitif terhadap konteks lokal agar lebih efektif.
“Intervensi harus menyasar tidak hanya ibu, tetapi juga keluarga dan komunitas, sekaligus memperkuat dukungan sistem, seperti kebijakan tempat kerja ramah ibu menyusui. Tanpa dukungan struktural, sulit mengharapkan perubahan perilaku yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan temuan kualitatif, riset ini memberikan gambaran komprehensif mengenai determinan sosial budaya ASI eksklusif.
“Temuan ini menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi komunikasi perubahan perilaku yang lebih efektif dan kontekstual. Sekaligus memperkuat kontribusi BRIN dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan pembangunan kesehatan berbasis data ilmiah,” katanya. (*)