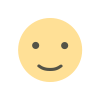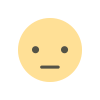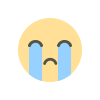Paradoks Guru – Berada di Tengah Tapi Dipinggirkan
Oleh: Martin Laurel Siahaan*

SAYA akan memulai tulisan ini dari fenomena Tri Wulansari, guru perempuan di SDN 21 Pematang Raman, Muaro Jambi yang dilaporkan ke Polisi karena menampar mulut muridnya.
Sekilas kasus yang terjadi Januari 2026 ini merupakan kesalahan guru dan kekerasan terhadap anak. Bagaimana sesungguhnya peristiwa ini terbentuk? Kita harus mulai dengan pertanyaan kritis agar dapat melihat dengan utuh.
Kedua, peristiwa MJ, guru agama di SMKN 1 Batam yang mencabuli murid laki-laki terjadi Januari 2026. Apakah peristiwa ini murni kesalahan guru dan pelecehan seksual terhadap anak?
Mari kita mulai membahas dua peristiwa ini sebagai fenomena dunia pendidikan Indonesia dalam paragraf-paragraf berikutnya.
Kedua peristiwa di atas memiliki ciri yang kuat. Tri Wulansari dan MJ menjadi guru di sekolah pemerintah, keduanya bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tri Wulansari merupakan seorang honorer dan MJ merupakan honorer yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam artian keduanya memiliki penghasilan dan kesejahteraan yang berbeda jauh dengan guru tetap.
Penghasilan sebagai guru honorer tingkat SD relatif lebih kecil sangat bergantung dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Berkisar antara Rp 400 ribu hingga Rp 1,5 juta tiap bulan. Sementara itu, penghasilan guru dengan status PPPK sesuai dengan Perpres No. 11 tahun 2024 adalah Rp3.203.600-Rp5.261.500.
Perbedaan besaran diterima hanya suatu fakta untuk menggambarkan bagaimana tenaga pendidik di Indonesia diperlakukan. Selanjutnya apa kaitan angka-angka di atas dengan peristiwa di atas. Bagaimana melihat peristiwa Tri Wulansari dan MJ sebagai sebuah kejahatan terhadap anak. Mari kita simak paragraf berikutnya.
Penelitian Liris Raspatiningrum dkk. (2025) menemukan guru mengalami kelelahan emosional kronis, stres akibat multi-peran dan konflik antara pengorbanan pribadi dan ketidakpedulian sistem.
Penelitian ini juga melaporkan banyak guru mengalami burnout etis, kelelahan akibat terus berbuat benar dalam sistem yang tidak mendukung.
Penelitian lain mengungkapkan kondisi guru di Indonesia berada dalam kelas pekerja prekariat atau prekaritas. “Prekaritas, yang didefinisikan sebagai upah rendah, ketidakamanan kerja, dan keterbatasan dukungan profesional” (Hidayati dkk., 2025).
Pada kasus Tri, murid ditampar karena mengucapkan kata-kata tidak pantas saat rambutnya dipotong. Praktik guru memotong paksa rambut murid laki-laki yang panjangnya melebihi ketentuan, lazim dilakukan di Indonesia. Dalam tradisi pendidikan di Indonesia hal tersebut disebut penegakan disiplin di sekolah.
Mendengar ucapan tersebut, Tri refleks menampar murid. Mari kita soroti khusus bagian ini. Tri menampar pasti karena kesal ataupun emosi. Setidaknya itu anggapan yang ada dalam pikiran sebagian pembaca. Bagaimana dengan MJ yang melecehkan siswanya?
Keterangan polisi menyebut murid laki-laki tersebut dilecehkan saat jam pelajaran berakhir di ruangan guru SMKN 1 Batam. Menurut polisi, MJ menghukum muridnya karena terlambat masuk kelas dan diminta untuk menemuinya di ruangan guru setelah jam sekolah usai.
Dalam tulisan ini saya tidak mengarah dogma dengan melihat dua peristiwa ini sebagai kasus pelanggaran pidana yang bersalah harus dihukum. Saya juga tidak ingin mengatakan salah satu guru salah dan yang lainnya benar. Peristiwa ini afirmasi bagi saya pekerjaan Guru di Indonesia teralineasi.
Baik Tri dan MJ saya melihat mereka melampiaskan sesuatu kepada muridnya ketika ada situasi yang menjadi pemicu. Ironi, kesehatan mental mereka diabaikan sebagai pekerja prekariat dalam dunia pendidikan yang fundamen membangun generasi bangsa.
Prekarisasi guru tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Penelitian Baihaqki dan Widiastuti (2018) menunjukkan bahwa guru kontrak bekerja di bawah bayang-bayang ketidakpastian, sehingga sulit merencanakan pengembangan profesional jangka panjang. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia dan warga negara.
Selain Tri dan MJ kita tahu, masih banyak fenomena-fenomena guru dan murid. Dimulai dari kekerasan fisik, verbal, dan kekerasan seksual. Banyaknya dan mudahnya kasus serupa ditemukan merupakan indikasi guru posisi sentral tapi termarginalisasi.
Praktik pendidikan di Indonesia semakin jauh dari Eudaimonia. Guru seharusnya diposisikan sebagai mentor pembentukan karakter yang kelak akan ditiru oleh muridnya. Pendidikan adalah tugas negara, dalam tulisan ini saya menegaskan esensi pendidikan adalah guru.
Guru merupakan nafas dari pendidikan itu, guru bukan pelaksana kurikulum, bahkan kurikulum yang tak pernah mereka buat—harus mereka laksanakan.
Untuk menutup bab ini, saya mengajak kita ke masa lalu dimana ketika Plato dan Aristoteles menjadi guru dan murid. Dalam tradisi pendidikan Plato dan Aristoteles, guru tidak pernah diposisikan sekadar sebagai pemberi informasi.
Guru adalah mentor—pembimbing jiwa dan karakter—yang mendampingi murid dalam menemukan kebenaran, membentuk kebajikan, dan menjalani kehidupan yang baik.
Di tengah pendidikan modern yang sering terjebak pada transfer materi dan capaian kognitif, warisan filsafat Yunani Kuno ini mengingatkan bahwa esensi pendidikan terletak pada relasi mentoring, bukan sekadar penyampaian pengetahuan. (*)
* Selain tim redaksi riaucerdas, penulis adalah Ketua Umum Barisan Rakyat 1
Juni/Barak 106